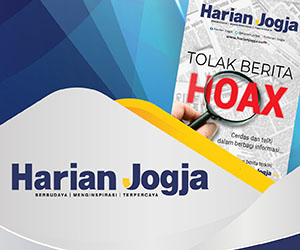Advertisement
OPINI: Proteksionisme Pangan
 Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis Indonesia - Rachman
Buruh melakukan bongkar muat karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/1/2023). Bisnis Indonesia - Rachman
Advertisement
India melarang ekspor beras non-basmati dan beras patah (broken rice) setelah Rusia menangguhkan partisipasinya dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative). Keputusan India pada 20 Juli 2023 itu berpotensi menekan pasokan beras global, yang kemudian akan diikuti kenaikan harga.
Perkiraan ini didasarkan pada fakta: India adalah pemasok 40% beras di pasar dunia. Sebagai eksportir utama beras, keputusan India yang lebih mengutamakan kebutuhan domestik bisa berdampak luas.
Advertisement
Pertama, sebagai eksportir utama beras di pasar dunia, India adalah penggerak utama harga pasar (price maker). Ini terjadi setelah India mengambil alih posisi Thailand sebagai jawara ekspor beras di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, langkah proteksionisme India mudah ditiru oleh negara lain.
Seperti penyakit menular, restriksi ekspor seperti ini biasanya bakal diikuti oleh negara-negara eksportir lainnya. Apalagi, Thailand dan Vietnam, eksportir beras nomor 2 dan 3 dunia, juga menghadapi persoalan yang sama dengan India dalam produksi padinya: terancam oleh El Nino.
Pada 2022, India mengekspor 22 juta ton beras. Dari jumlah itu, volume jenis beras yang dihentikan ekspornya mencapai 10 juta ton. Sementara jenis beras pratanak (parboiled) yang jumlah ekspornya 7,4 juta ton pada 2022 tetap bisa diekspor.
Pasar beras di dunia itu tipis dan bersifat residual stock atau stok sisa. Jika volume ekspor yang dilarang India mencapai 10 juta ton beras, potensial mengguncang pasar. Negara-negara yang selama ini menggantungkan pasokan beras dari India bakal terkena imbas langsung.
Langkah proteksionisme India yang membatasi ekspor beras bukan hal baru. Pada September 2022, India menutup ekspor beras patah. Ini ditempuh untuk mengendalikan harga beras domestik.
Kala itu, panen padi India turun sekitar 6,6% (8,64 juta ton beras) karena pola hujan tak merata. Rangkaian kebijakan proteksionisme ini adalah bagian dari respons pemerintah India untuk memastikan kebutuhan domestik pada prioritas pertama. Langkah proteksionisme India ini, merujuk ekonom New York University, Nouriel Roubini dalam Great Depressions (2020), adalah 1 dari 10 gejala depresi ekonomi.
Proteksionisme di bidang pangan, yang tak lain adalah lawan globalisasi itu, juga bukan hal baru. Saat krisis pangan 2007—2008 dan 2011, resep generik itu selalu diulang.
Dalam dua periode krisis itu, krisis pangan disulut oleh produksi serealia yang menurun dan daya beli warga yang rendah, yang kemudian diikuti ekspektasi penurunan suplai pangan di pasar dunia. Ketika pintu ekspor ditutup, pasar panik, dan harga-harga pangan meroket. Saat krisis pangan 2008, restriksi ekspor pangan berlangsung setahun.
Pada posisi puncak, restriksi oleh 18 negara mewakili 16,4% total kalori yang diperdagangkan di dunia. Plus krisis energi dan spekulasi di pasar komoditas, krisis pangan kian dalam.
Saat pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina, restriksi ekspor juga terjadi. Saat Covid-19 pembatasan ekspor dilakukan oleh 20 negara mewakili 7% dari total kalori yang diperdagangkan di dunia.
Pembatasan ekspor hanya berlaku 3 minggu, sehingga tak berbuah krisis pangan akut. Kala perang Rusia-Ukraina terjadi, restriksi ekspor pangan dilakukan 25 negara sekitar 45 minggu mewakili 9,81% dari total kalori yang dijual di pasar dunia. Dibandingkan Covid-19, dampak perang Rusia-Ukraina lebih terasa.
Proteksionisme pangan ini diyakini akan selalu melekat mengiringi bandul gerak geopolitik global. Ini seiring tiga ciri utama yang melekat pada geopolitik pangan dunia.
Pertama, industri pangan dan perusahaan transnasional (TNCs) yang hanya fokus pada sedikit spesies. Kedua, TNCs membentuk rantai pangan (agrifood chain). Rantai ini menghubungkan dari sejak gen, bibit, input agrokimia, produksi pangan dan serat, trading dan pengolahan bahan mentah, prosesing dan manufaktur hingga rak-rak di supermarket.
Ketiga, konsentrasi pangan global di segelintir pelaku yang jauh dari pasar sempurna dan mengarah monopoli. Konsekuensinya serius: harga pangan di pasar dunia tak stabil.
Konsekuensi arsitektur pangan seperti ini, pertama, instabilitas jadi keniscayaan. Krisis pangan 2007—2008 dan 2011 jadi bukti: harga bergerak bak roller coaster.
Kedua, krisis pangan berulang. Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik, yang tidak jarang diikuti jatuhnya sebuah rezim. Sebagai importir pangan yang besar, tahun 2021 mencapai US$25 miliar, nasib Indonesia sejatinya tak lebih baik dari negara-negara di jazirah Arab yang menggantungkan 90% pangannya dari impor.
Berulangnya resesi, krisis atau pandemi adalah keniscayaan. Ketika dihadapkan pada resesi, krisis atau pandemi negara-negara eksportir pangan akan mementingkan kepentingan domestik. Proteksionisme pangan akan selalu berulang dan menjadi resep generik. Pertarungan dalam memenuhi dan mengontrol ketersediaan pangan akan jadi penentu gerak bandul geopolitik global.
Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestik. Merujuk amanat UU Pangan No. 18/2012, Indonesia wajib berdaulat di bidang pangan. Ini bisa dilakukan dengan memberi akses petani pada sumber daya produktif, menata ulang cara berproduksi, tata niaga, dan tata konsumsi. Jika ada kemauan kuat, tidak ada kata yang tidak mungkin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement