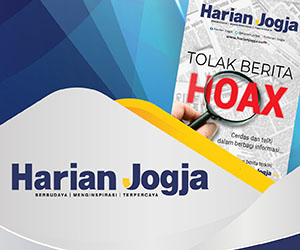Advertisement
Refleksi Satu Dekade Jogja Kota Batik Dunia
 Doddy Junianto, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi DIY
Doddy Junianto, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi DIY
Advertisement
Hari Batik Nasional yang ditetapkan setiap 2 Oktober bukan sekadar perayaan kain bermotif indah, melainkan momentum reflektif untuk meneguhkan kembali jati diri bangsa. Batik tidak hanya dipandang sebagai karya estetika, tetapi juga sebagai artefak budaya yang mengandung nilai historis, filosofis, dan ekonomis.
Di tengah derasnya arus globalisasi, batik hadir sebagai simbol resiliensi budaya tradisi yang mampu beradaptasi sekaligus berinovasi. Bagi masyarakat Yogyakarta, peringatan Hari Batik Nasional semakin bermakna karena kota ini sejak 2014 telah menyandang predikat World Batik City dari World Craft Council (WCC).
Advertisement
Predikat tersebut bukan hadiah simbolis, melainkan pengakuan internasional terhadap ekosistem batik Yogyakarta yang kompleks dan berkelanjutan. WCC menilai Yogyakarta layak menyandang predikat World Batik City karena memenuhi tujuh unsur utama: warisan budaya (heritage) yang terjaga, kemampuan adaptasi dengan perkembangan zaman (contemporary), praktik keberlanjutan (sustainability), kontribusi ekonomi (economy), keberadaan komunitas perajin yang tangguh (craftspersons), inovasi berkelanjutan (innovation), serta jejaring pemasaran global (marketing).
BACA JUGA: JIBB 2025: Gaungkan Spirit Pelestarian Batik lewat Dunia Pendidikan
Dari para perajin batik tulis di sentra/desa, dan pengusaha batik cap, hingga akademisi dan komunitas kreatif, seluruh aktor berperan dalam menjaga dan mengembangkan ekosistem tersebut. Batik Jogja tidak sekadar wastra bermotif, melainkan representasi pengetahuan tradisional yang sarat makna kehidupan. Motif parang, kawung, atau lereng, misalnya, dapat dipahami sebagai teks budaya yang menyimpan narasi filosofis tentang keteguhan, kesederhanaan, serta etika hidup masyarakat Jawa.
Namun, pengakuan global tersebut sekaligus menghadirkan konsekuensi: bagaimana menjaga keberlanjutan batik agar tetap relevan bagi generasi kini, sekaligus mampu menjawab tantangan industri kreatif kontemporer.
Di sinilah gerakan Bangga Buatan Jogja (BBJ) memperoleh urgensinya. Sebagai turunan dari program nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), BBJ berfungsi sebagai instrumen sosio ekonomi yang mengonsolidasikan dukungan masyarakat terhadap produk lokal.
Konsumsi batik Jogja dalam kerangka BBJ bukan hanya praktik konsumtif, melainkan tindakan afirmatif untuk memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus memperluas basis keberlanjutan budaya. Gerakan ini menegaskan prinsip bahwa membeli dan mengenakan batik Jogja adalah bagian dari civil responsibility, yakni keterlibatan warga dalam mendukung ekosistem industri kreatif.
Apalagi dalam konteks persaingan pasar global yang semakin kompetitif, preferensi konsumen domestik terhadap produk lokal dapat dipandang sebagai modal sosial yang strategis.
Tahun 2025 menjadi tonggak penting karena Yogyakarta kembali menggelar Jogja International Batik Biennale (JIBB) yang kelima. Sejak awal penyelenggaraannya, JIBB telah berperan sebagai ruang epistemik dan kultural, bukan sekadar etalase pameran. Ia menghadirkan diskursus akademis, peragaan busana, hingga lokakarya yang mempertemukan perajin, peneliti, pelaku usaha, serta jejaring internasional.
JIBB membuktikan bahwa batik dapat berfungsi ganda: sebagai medium ekspresi artistik dan sebagai komoditas industri yang bernilai ekonomi tinggi. Lebih jauh, pelaksanaan JIBB 2025 juga bertepatan dengan satu dekade penetapan Yogyakarta sebagai World Batik City.
Momentum ini menjadi ruang evaluatif sekaligus strategis, menimbang bagaimana batik Jogja mempertahankan statusnya sebagai warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage), sekaligus mengembangkan diri menjadi industri berdaya saing global.
Tantangan yang dihadapi antara lain modernisasi produksi, digitalisasi pemasaran, hingga pemenuhan standar ramah lingkungan semuanya menuntut transformasi berbasis riset dan inovasi.
Dalam konteks tersebut, sinergi multipihak menjadi kunci. Pemerintah daerah, perajin, akademisi, komunitas kreatif, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang sistematis.
Filosofi Jawa mengajarkan hamemayu hayuning bawana usaha menjaga harmoni dan memperindah dunia yang relevan sebagai paradigma pembangunan ekosistem batik.
Semangat inilah yang perlu diinternalisasikan: batik bukan hanya dilestarikan, tetapi juga ditumbuhkan agar tansah tumuwuh mengikuti dinamika zaman. Dengan demikian, batik dapat dipahami sebagai pranata budaya yang memadukan dimensi tradisi dan modernitas, lokalitas dan globalitas, spiritualitas dan ekonomi.
Peringatan Hari Batik Nasional, predikat Yogyakarta sebagai World Batik City, gerakan BBJ, serta penyelenggaraan JIBB 2025 sesungguhnya adalah simpul-simpul perjuangan kolektif. Semua itu tidak berhenti pada seremoni simbolik, melainkan harus diwujudkan dalam strategi kultural, sosial, dan ekonomi yang konkret.
Akhirnya, batik bukan hanya milik para perajin, tetapi milik seluruh masyarakat yang bangga mengenakannya, mendukung produksinya, serta mewariskannya. Dari Yogyakarta, dunia belajar bahwa selembar kain dapat menuturkan peradaban. Dari batik pula, bangsa ini meneguhkan identitas sekaligus menapaki jalan menuju kemandirian industri kreatif yang berakar pada budaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Dana Pokir DPRD Kulonprogo 2026 Minim, Infrastruktur Terancam
Advertisement

Jennifer Coppen Pilih Diam soal Sindiran The Connel Twins
Advertisement
Advertisement
Advertisement