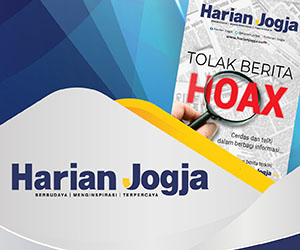Advertisement
Berhenti Sejenak: Tubuh dan Dunia Tanpa Jeda
 Penampilan empat pantomimer dalam pementasan Laboartorium Obah 3 bertajuk Berhenti Sejenak di Auditorium IFI LIP, Sabtu (24/8). - Harian Jogja/Arief Junianto
Penampilan empat pantomimer dalam pementasan Laboartorium Obah 3 bertajuk Berhenti Sejenak di Auditorium IFI LIP, Sabtu (24/8). - Harian Jogja/Arief Junianto
Advertisement
There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy. (Camus, 1942, The Myth of Sisyphus). Hidup modern, dengan percepatan tanpa henti, sering kali menyerupai kerja Sisyphus: mendorong batu ke puncak hanya untuk jatuh lagi, begitu seterusnya tanpa akhir.
Advertisement
Panggung temaram. Penonton baru saja menghambur masuk ke dalam ruangan.
Belum juga mereka meletakkan pantat di tribune, seorang performer berdiri di bawah sorotan lampu. Lengan kanannya menekuk. Jemarinya bergerak-gerak seperti hendak membuka pintu. Mungkin dia tengah membayangkan kenop pintu yang susah dibuka, atau memang dirinya sendiri yang tak mampu menentukan pilihan: keluar atau tetap terjebak di dalam.
Adegan itu membuka pementasan Laboartorium Obah #3 bertajuk Berhenti Sejenak yang digelar oleh Sanggar Seni Asrita di Auditorium IFI LIP Jogja, Sabtu (24/8).
Selanjutnya, dua orang bersijingkat menuruni level panggung, sedangkan satu orang lainnya, tertinggal di atas panggung dengan lampu sorot yang perlahan meredup.
Dua orang di bawah, memilih tempatnya sendiri-sendiri, bergerak dengan ritme masing-masing. Salah satunya bergerak seolah memasuki sebuah ruangan dengan berbagai kecanggihan teknologi di dalamnya: monitor layar sentuh, platform virtual reality, dan tombol mekanis berbunyi beep beep saat ditekan.
Secara berulang-ulang, dia menonton adegan-adegan yang nyaris sama, mulai dari jamuan makan, konten olahraga, hingga konten-konten narsistik lain. Hanya mimik wajah yang ia tunjukkan lah yang menunjukkan sedikit perbedaan di setiap adegan itu, meski muaranya tetap sama: absurd dan membosankan.
Orang kedua lalu disorot lampu. Kali ini dia menunjukkan kecemasan, bahkan sesekali ketakutan.
Dengan nafas terengah, dia terus berlari, seperti hendak sembunyi dan melarikan diri, bisa jadi dari sesuatu, seseorang, atau mungkin bisa jadi, sekelompok.
Seperti itulah semesta yang digambarkan oleh tiga performer yang sudah bergerak lebih dulu. Semesta yang absurd, membosankan dan penuh dengan kecemasan. Semesta yang seolah tak pernah punya jeda. Di situlah mereka seperti gagal menjadi manusia.
Lampu panggung mendadak menyorot seorang performer. Dia duduk bersila tepat di tengah panggung. Tangannya lalu bergerak, seolah menari, seolah pula melambai-lambai seperti tengah meminta tolong.
Saat berdiri, tangannya mengarah ke bagian perut, seperti hendak menarik sebuah kain dan membebatkannya dengan erat. Semakin banyak putaran bebatan, semakin pula dia merasa kain itu menekan perutnya.
Tubuhnya lalu terjatuh. Mimik wajahnya meringis seperti terjebak antara sakit dan kecewa. Sakit karena menahan pedih karena perut yang terbebat erat, dan kecewa karena kegagalannya menolak rasa sakit itu.
Lagi-lagi, begitulah dunia. Dia seperti mencelikkan mata penonton, bahwa dunia memang terus melangkah tanpa jeda, tanpa memberi kesempatan pada manusia untuk sekadar mencintai dan mengenal dirinya sendiri.

Performer itu seperti menampilkan rekaman adegan yang jamak dialami oleh banyak manusia. Kebiasaan dan tradisi menyakitkan yang lantas dinormalkan karena memang sesuatu yang baik menurut mereka, adalah hal baik yang wajib hukumnya untuk dilakoni, tak peduli sesakit apa yang kita rasakan. Sebab begitulah cara dunia bekerja.
Estetika Jeda
Di sinilah letak kekuatan pertunjukan yang mereka tampilkan–setidaknya hingga 5-10 menit awal.
Pada beberapa bagian pertunjukan yang disutradarai oleh Ari “Inyong” Dwianto tersebut, penonton seperti dipaksa menatap tubuh yang nyaris tak bergerak, hanya bergetar halus karena napas atau tegangan otot. Situasi itu menimbulkan rasa tidak nyaman sekaligus membuka ruang tafsir.
Hidup modern, dengan percepatan tanpa henti, sering kali menyerupai kerja Sisyphus: mendorong batu ke puncak hanya untuk jatuh lagi, begitu seterusnya tanpa akhir
Sampai di sini, saya merasa pertunjukan berjalan dengan tempo yang lambat, meski alur yang disajikan tetap dinamis. Titik pertemuan antara romansa, dan tragedi ditandai dengan baik oleh musik yang terdengar tidak berlebihan tetapi tepat sasaran.
Para penampil tidak serta-merta menampilkan gerak yang gemerlap dan meletup-letup. Sebaliknya, mereka menunda, menahan, bahkan menggantung setiap gerakan pada titik-titik yang rapuh.
Seorang penari berdiri lama dengan tangan terangkat, jari-jarinya bergetar seperti nyiur bergerak halus oleh angin yang mengembus. Yang lainnya, menunduk, menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Di sinilah saya, seperti diajak–bukan dipaksa, merasakan betapa absurdnya dunia yang terus bergerak tanpa jeda.
Lewat gerak keempatnya, tubuh menjelma ruang refleksi: rentan, rapuh, resah, sekaligus juga penuh daya. Mereka seperti bercakap dalam diam lewat tubuh. Itu seperti mampu mengubah jeda menjadi kata, dan hening menjadi kalimat panjang.
Begitulah, ingatan saya kemudian melayang pada sesosok bernama Albert Camus. Baginya, absurditas lahir ketika manusia mencari makna dalam dunia yang menolak memberikannya. Kehidupan modern, dengan percepatannya yang tiada henti, sering kali terasa persis seperti absurditas itu sendiri: sebuah mesin yang terus bergerak tanpa arah jelas, menuntut manusia mengikuti irama tanpa sempat bertanya untuk apa, tanpa sempat untuk sekadar mencintai dirinya sendiri.
Sampai di titik ini, saya merasa keempat performer cukup berhasil menelanjangi absurditas dunia itu. Dalam diam, saya seperti mendengar rintihan keempatnya, “Beginilah rasanya ketika kita bergerak dalam dunia tanpa jeda, membosankan, melelahkan, menyakitkan.”

Membaca Decroux
Menonton Laboartorium Obah #3: Berhenti Sejenak, saya seperti menonton sisi lain dari pentas Laboartorium. Di sini pantomim tak lagi ditampilkan dengan gerak monoton, riasan putih di wajah, baju loreng hitam-putih, dan mimik wajah yang begitu-begitu saja.
Keempat performer seperti hendak membongkar konsep itu semua. Mereka seolah menampilkan teknik berpantomim secara lebih kompleks.
Di sinilah mereka menjadikan tubuh sebagai alat berkomunikasi, sebagai satunya-satunya bahasa. Fleksibilitas gerak, mulai dari melompat, berjumpalitan, hingga berjalan ala robot dan sesekali moonwalk, menjadi menu wajib yang membuat gerak mimikri mereka menjadi lebih komunikatif.
Ternyata benar. Dari obrolan bersama para performer, seusai pertunjukan, dugaan saya tidak meleset. “Mereka sedang bereksperimen dengan metodenya Decroux,” pikir saya tepat seusai pertunjukan.
Etienne Decroux (1988-1991) dengan konsep mime corporel dramatique yang ia dengungkan pada akhir 1920-an. Konsep dan metode itu lahir sebagai bentuk kritik atas pantomim tradisional yang cenderung sentimental, bahkan–meminjam diksi Decroux–imitatif.
Bagi Decroux, tubuh sejatinya teks dramatik itu sendiri. Baginya, otot, sendi, dan gestur merupakan kata-kata dan bahasa yang bisa ditangkap dan diterjemahkan.
Menonton Laboartorium Obah #3: Berhenti Sejenak, saya membayangkan tentang sekelompok pantomimer tengah mencoba menerapkan metode yang dipakai oleh Decroux, mulai dari prinsip segmentasi tubuh lewat upaya pengisolasian bagian tubuh tertentu, seperti misalnya kepala, dada, panggul, dan kaki yang digerakkan secara independen atau saling menahan; adegan ketika tubuh-tubuh mendadak membeku, dan hanya dada yang membahasakan sengal nafas; hingga gerak tubuh yang lebih dari sekadar mimesis atas gerak sehari-hari.
Itulah sebabnya, lewat pentas tersebut, saya seperti menangkap sinyal yang diresonansikan oleh performer. Saya seperti ikut merasakan spirit dasar Decroux dalam panggung Laboartorium Obah #3 malam itu: menjadikan tubuh sebagai sebagai dramaturgi, menjadikan gerak sebagai bahasa kritis.
Hanya saja, ada sedikit celah dalam Berhenti Sejenak, terutama ketika saya berusaha mengidentikkannya dengan metode dan konsep mime corporel dramatique.
Celah ini sangat terlihat dan terasa ketika prinsip Decroux terkait dengan immobilite parlante (kebekuan yang bicara) mereka terapkan di atas panggung. Pada prinsip ini, tubuh para performer di satu momen hanya berdiri membeku, tanpa suara, hanya sengal nafas yang terdengar.
Seharusnya, kebekuan itu bukan kosong, melainkan intensi dramatik sekaligus sebuah pernyataan tubuh tentang absurditas dunia yang tak pernah berhenti bergerak.
Namun, dalam pementasan tersebut, saya melihat performer acap gagal dalam menampilkan intensi itu. Kebekuan yang mereka adegankan, dan sengal nafas yang mereka adegankan, tak sekadar dari upaya mereka menjeda gerak demi bisa mengatur nafas, tak terlihat adanya tendensi untuk merefleksikan konsep “jeda” seperti yang saya inginkan.
Setidaknya ini membuktikan bahwa untuk menerapkan metode Decroux dalam sebuah pementasan, memerlukan endurance stamina yang benar-benar prima. Sayangnya, keempat performer sepertinya kurang mempersiapkan diri untuk tantangan tersebut.
Selain itu, ada pula titik kerentanan yang muncul dalam pementasan malam itu. Lagi-lagi saya melihatnya ada pada penerapan immobilite parlante. Sejak kepala saya terisi oleh sosok Decroux saat menonton Berhenti Sejenak, kekhawatiran saya yang paling utama adalah bagaimana saya dan penonton lainnya bisa memaknai pesan jeda yang disampaikan oleh para performer.
Tentu saja, agar pementasan tersebut tidak arbitrer, maka diperlukan strategi komunikasi artistik yang tepat. Dengan begitu, pesan jeda pun bisa diterjemahkan secara optimal oleh penonton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Digitalisasi Musisi Jalanan Malioboro, Kini Bisa Diapresiasi Nontunai
Advertisement

VinFast Luncurkan 4 Skuter Listrik 2026 dengan Sistem Swap
Advertisement
Advertisement
Advertisement