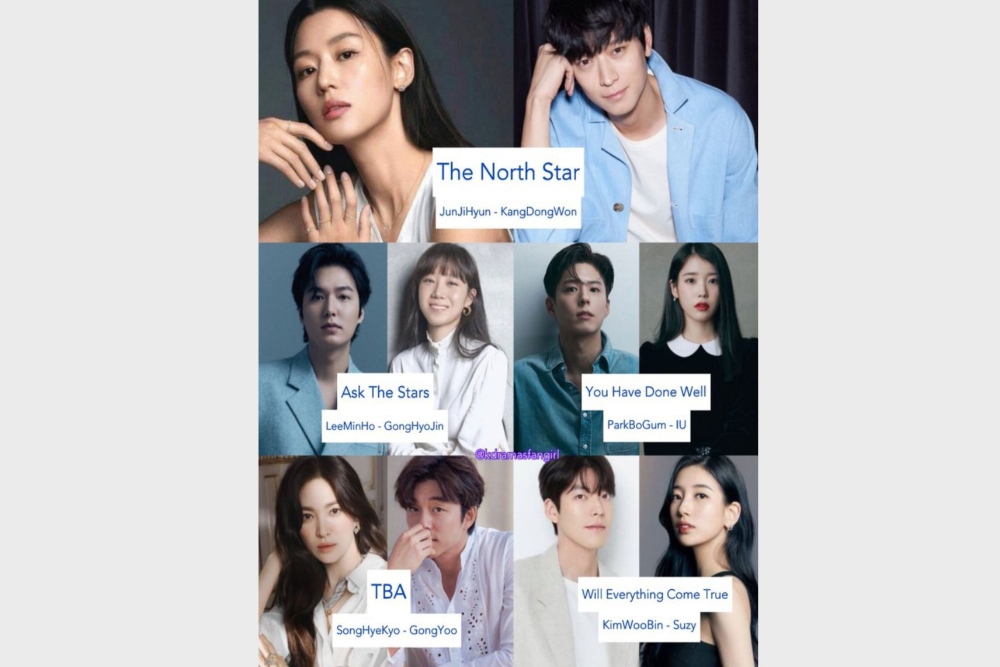Advertisement
OPINI: Keluarga Besar Pemudik Modern
 Pemudik sepeda motor. - Bisnis Indonesia/Rachman
Pemudik sepeda motor. - Bisnis Indonesia/Rachman
Advertisement
Arus gerak mudik/balik mendefinisikan ulang keluarga besar manusia. Di Indonesia, manusia masih berusaha mempunyai tautan kekeluargaan secara vertikal dan horizontal yang jauh memanjang dan menyentuh masa lalu: mbah canggah, mbah buyut, kakek, nenek, ibu dan bapak, pakde, bude, paklik, dan seterusnya.
Tidak cuma ibu-bapak-anak plus kakek-nenek dalam model keluarga (batih) modern yang sering terlihat sangat jauh sekali secara emosional. Mudik barangkali semacam kembalinya keluarga besar manusia di zaman gerak cepat modernitas yang terus berusaha membuat institusi keluarga menuju senja kala.
Advertisement
Dalam arus mudik kali ini sekitar 33 juta (tahun lalu sekitar 17 juta) manusia kembali menemui dan menemukan keluarga mereka. Mudik barangkali adalah ritus kekeluargaan manusia melawan gerak modernitas yang memerosokkan manusia pada satuan individu-individu saja, bahkan mudik adalah semacam intervensi kolosal terhadap hasrat modernitas yang hanya menawarkan keluarga batih.
Modernitas tak mengakui ibu dari kakek nenek apalagi para leluhur keluarga yang terbaring di kuburan. Hanya anak + ibu atau anak + bapak seperti dalam banyak iklan kapitalistis yang sungguh menggoda.
Memang harus disadari bahwa keluarga batih menjadi gejala yang sangat dominan secara global. Ini seperti dilaporkan majalah Time edisi April 2004 yang bukan hanya kisah masyarakat Barat (Eropa atau Amerika), tapi juga sudah melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia.
Sebuah fenomena keluarga yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan menurut berita terbaru, peristiwa perceraian tercatat dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, meningkat 52% dengan 70% diajukan sang istri (Kompas, 30 Juni 2015).
Arus modernitas belum bisa melumpuhkan keluarga secara total, meski kita terus dipaksa menjadi manusia urban, menjadi manusia modern. Hidup kita yang dilecut dengan modernitas urban dipaksa keluar dari kampung dan desa, menjadi manusia urban yang bergerak mempercepatkan segalanya.
“Menjadi modern” di pusat-pusat kota, seperti dikatakan Berman (1982), berarti mendapati diri kita dalam lingkungan yang menjanjikan petualangan, kekuasaan, kegembiraan, pertumbuhan transformasi diri dan dunia kita.
Kita terlecut hasrat kemakmuran hidup, dengan segala dalihnya, termasuk demi kebahagiaan keluarga. Tetapi, di balik semua itu, menurut Berman, pada saat yang sama mengancam dengan merusak segala yang kita punya, segala yang kita ketahui, segalanya dari diri kita.
Masa Lalu
Dalam arus mudik, kita kembali ke masa lalu, kembali pada diri kolektif yang hendak tak diakui modernitas, menemui keluarga besar dengan segala masa lalunya. Para pemudik ini merasa harus menziarahi dan mendoakan orang-orang dalam keluarga yang tak pernah ditemui sama sekali, yang tentu saja tak sangat penting bagi modernitas kapitalistis dan hidup urban.
Kita tak selamanya hendak bergerak ke depan dengan cepat dalam renggutan kuasa kultural ekonomis. Kita ingin surut ke belakang, bahkan masih bertaut dengan para anggota keluarga yang sudah lama meninggal—tapi bukan tiada. Keluarga mutakhir memang tak lagi punya imajinasi keluarga berleluhur yang panjang menjangkau ikatan keluarga masa lalu.
Para leluhur itu sudah dihapuskan oleh modernitas. Kita ingat revolusi berkeluarga dengan dalih komunisme-sosialisme yang pernah dicoba di Rusia. Revolusi ini, seperti yang dikritik dengan tajam oleh Leon Trotsky (2010: 163), hendak membuat satu langkah heroik untuk menghancurkan apa yang disebut “rumah tangga”—institusi yang usang, jenuh, dan stagnan.
Komunisme menuduh keluarga sebagai sarang ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang terus dibela dan disahkan. Sosialisme-komunisme mengajukan doktrin hubungan antarmanusia tanpa keserakahan, persahabatan tanpa kecemburuan dan intrik, cinta tanpa perhitungan untuk diri sendiri.
Seperti kontradiksi yang juga terus melanda komunisme-sosialisme pada masa itu, salah satu bab yang sangat dramatis dalam buku besar tentang Uni Soviet pastilah berkisah tentang keruntuhan dan pecahnya keluarga-keluarga Soviet. “Kebiadaban yang dimunculkan oleh kekuasan dan uang dalam hubungan antarkelamin berkembang subur di jajaran birokrasi Soviet,” kata Trotsky (2010: 175-6), bahkan mengungguli kaum borjuasi Barat dalam hal ini.
Revolusi komunisme itu tidak berhasil menghancurkan keluarga, malah menyadarkan makna eksistensi keluarga. Sekarang kita hidup dalam napas kapitalisme, antitesis komunisme, juga demokrasi yang mengagungkan hak individu. Di sini, sedikit banyak ada nuansa antikeluarga bahkan benih-benih penghancur keluarga, meski memang tidak secara total.
Malah ada semacam kemesraan antara kapitalisme dan institusi keluarga. Kita tentu saja begitu akrab dengan iklan-iklan kemesraan berkeluarga dengan menjadi kelurga konsumen segala produk kapitalistis. Benda-benda inilah yang sekarang menjadi guru besar keluarga mutakhir. Kita sungguh susah menampiknya, termasuk pada saat hari yang disucikan.
Ikatan Emosional
Yang dihilangkan dan tak hendak diakui kapitalisme adalah ketulusan naluriah yang bisa terjadi antara seorang ibu-bapak terhadap anak-anaknya tanpa melalui benda-benda (ikatan emosional kepada para leluhur). Seperti senyum, tawa, atau tangis bayi, atau seperti getaran rasa kasih seorang kakek-nenek yang entah berapa lama lagi bisa bertahan hidup saat melihat gerak tawa cucu mereka.
Hal-hal ini melampaui nilai dan harga dalam sistem kapitalisme. Peristiwa keluarga yang tak hendak mengakui peran kapitalisme ini bisa saja dituduh sebagai angan-angan esensialistis yang menuduh bahwa keluarga adalah hanya konstruksi manusia belaka, bukan asali, yang direkayasa dan penuh kuasa yang tak emansipatif.
Mungkin ada benarnya, tetapi pertaruhan yang harus dikorbankan untuk merekonstruksi (apalagi merevolusi) keluarga, kita sadar, harga plus nilainya sungguh terlalu mahal, baik bagi si miskin atau si kaya, baik secara personal atau komunal. Kita sungguh membutuhkan institusi keluarga. Apa pun yang terjadi, seberapa pun harganya.
Kita sadar apa pun bisa dipertaruhkan untuk masa depan manusia yang tak membutuhkan kuasa keluarga, baik dalam bentuk peradaban, kebudayaan, negara, atau sekadar “keluarga” dan tiap yang melawan kaidah sosial ini tampaknya sering harus mengelus dada dalam-dalam sejak masa bayi.
Secara ambivalen, mungkin bisa dikatakan bahwa pada akhirnya modernitas yang melahirkan teknologi transportasi juga dipaksa mengakui keluarga besar manusia. Keluarga yang bergerak dalam arus mudik terlepas ikatannya yang bertaut dengan kerja ekonomis, politik kekuasaan, atau gaya hidup berurban.
Kita barangkali tak hendak menemui kolega kerja, mitra bisnis, kawan koalisi politik, teman kantor, sahabat di pabrik, dan sebagainya. Kita sedang menuju pada keluarga kita masing-masing. Ada kerinduan seorang kakek-nenek pada senyum penuh gairah cucu: ada bapak-ibu yang menunggu anak-anak di rumah dengan penuh aura kehangatan yang tak harus diperantarai kepentingan yang bersifat duniawi.
Ada saudara kandung yang lama terpisah akibat kerja; ada saudara ibu-bapak dan saudara kakek-nenek; ada anak-anak yang merindukan bapak, ibu, kakek, nenek; ada sekian banyak manusia di kuburan yang masih dianggap hadir dan perlu disapa dengan doa dalam kehidupan ini. Belum ada kuasa modernitas yang berhasil menghilangkan apalagi menghancurkannya. Kita ada dalam naungan kasih keluarga.
*Penulis meminati tema filsafat pendidikan, ekonomi politik, dan filsafat agama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Solopos
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
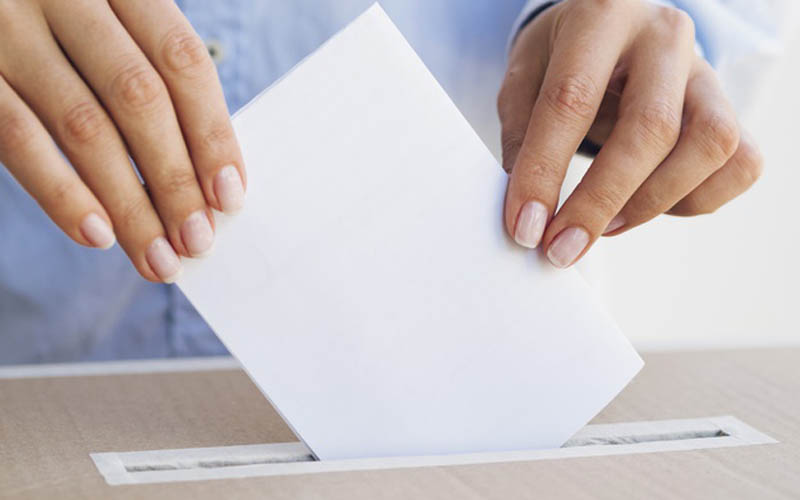
Muncul Wacana Pilihan Lurah di Gunungkidul Tahun Depan Digelar Dua Kali
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement